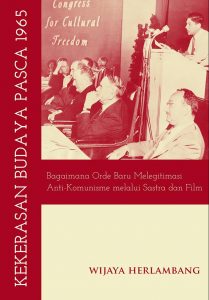Pasca Perang Dunia II, pergumulan dua negara adidaya pemenang perang tersebut, Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet terlibat dalam perang dingin yang panas. Kedua negara ini akhirnya saling menaruh rasa curiga dan dunia kala itu berada pada kondisi dalam ancaman bayangan perang nuklir yang dimiliki kedua negara tersebut.
Menurut Robert McNamara dalam Lilik Salamah, konflik Perang Dingin ini terjadi karena AS menganggap Uni Soviet dengan ideologi komunis dan penekanan “Socialism in One Country” ingin menguasai dunia secara revolusioner dan anti-kapitalis.[1] Hal tersebut membuat AS ketar-ketir, ditambah semakin menjamurnya peralihan beberapa negara yang menjadi negara komunis.
Melihat kenyataan ini, AS berusaha mengekang pengaruh komunisme Uni Soviet dengan melakukan strategi-strategi melalui penyebaran ideologi liberalisme-demokrasi sebagai ideologi negara yang dianggap humanis dengan secara bersamaan menyebarkan isu tentang bahaya komunisme.
Di tahun 1960an, Indonesia lebih memilih membangun –dan bergabung bersama negara-negara lain— dalam sebuah blok yang dinamakan Non-Blok ketimbang bergabung Blok Barat (AS) atau Blok Timur (Uni Soviet). Kendati demikian, pada kenyataanya Soekarno yang kala itu menjadi “simbol Indonesia” akhirnya memang agak lebih condong dengan kubu Blok Timur Uni Soviet.
Hal tersebut tentu saja menimbulkan kecurigaan AS, ditambah Partai Komunis Indonesia pada masa itu sedang berada pada fase puncaknya. Inilah yang akhirnya membuat AS berupaya untuk menghalau laju pengaruh komunisme dengan menyediakan bantuan militer dan ekonomi untuk Indonesia.
Bahkan, ketika Blok Timur mengindikasikan keinginan untuk membangun kerjasama dengan Indonesia, pemerintah AS memberikan otoritas yang hampir tanpa batas kepada CIA (Central Intelligence Agency) untuk menyalurkan dukungan keuangan guna menggelar operasi rahasia di Indonesia seperti menyuap musuh-musuh politik Sukarno, membeli suara untuk memenangkan Pemilu 1955, dan termasuk membantu aktivitas pendidikan dan kebudayaan melalui institusi-institusi filantropi dan kebudayaannya dengan membangun aliansi anti-komunis.[2]
Dalam bukunya yang berjudul Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme melalui Sastra dan Film, Wijaya Herlambang mengatakan bahwa gagasan untuk menggunakan kebudayaan sebagai alat propaganda AS dalam menyebarkan paham liberalisme-demokrasi dan anti komunisme merupakan bagian dari kebijakan politik luar negeri AS untuk melawan Marxisme dan komunisme di seluruh dunia, dari mulai negara-negara Eropa, kemudian diperluas ke negara-negara Afrika, Amerika Latin, dan Asia termasuk Indonesia. Gagasan ini disebut Frances Stonor Saunders sebagai Perang Dingin Kebudayaan.[3]
Berdirinya CCF dan pengaruhnya dalam Sastra Indonesia
AS melalui CIA mendirikan organisasi yang fokus mempromosikan liberalisme sebagai ujung tombak melawan komunisme di bidang kebudayaan, yaitu CCF (Congress for Cultural Freedom). CCF didirikan di Berlin pada tahun 1950 oleh agen CIA, Michael Josselson. Organisasi ini dikendalikan oleh OPC (Office of Policy Coordination) yang dikepalai oleh Frank Wisner di bawah arahan Direktur CIA, Allen Dulles.[4] Misi utama dari CCF sendiri ialah bertujuan untuk melepaskan segala keterkaitan seniman dan intelektual di seluruh dunia dari komunisme melalui gagasan “kebebasan berekspresi” sehingga menciptakan landasan dasar filosofis bagi para intelektual untuk mempromosikan kapitalisme barat dan anti-komunisme.
Pada Februari 1955 di Rangoon, CCF mengadakan konferensi di Asia untuk pertama kalinya, serta mengundang Mochtar Lubis (Pemimpin harian Indonesia Raya 1949-1974) dan simpatisan Partai Sosialis Indonesia (PSI) lainnya seperti redaktur majalah Konfrontasi, —yang disebut Keith Foulcher sebagai media lalu lintas kebudayaan antara Indonesia dan Barat dalam kaitannya dengan pencarian identitas kebudayaan Indonesia dalam konteks nasionalisme pasca-perang—Sutan Takdir Alisjahbana. Salah satu hasil konferensi adalah terbentuknya komite interim dengan Mochtar Lubis dan Sutan Takdir Alisjahbana sebagai anggotanya pada 1956.
Kiprah Mochtar Lubis di CCF membuat dirinya dekat dengan Ivan Kats, perwakilan CCF untuk Program Asia yang memiliki peran sebagai salah satu penghubung penting antara intelektual Indonesia anti-komunis dan organisasi filantropi raksasa seperti Rockefeller dan Ford Foundation. Ivan Kats juga punya peran untuk mendistribusikan buku-buku yang direkomendasikan CCF kepada komunitas intelektual di Indonesia seperti karya-karya eksistensialis anti-komunis Albert Camus dan Miguel de Unamuno, lalu karya George Orwell Animal Farm (1957) dan kumpulan esai anti komunis The God That Failed (1949) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh CCF.
Kats mengirimkan buku-buku kepada 20 perpustakaan di Indonesia dan kepada lebih dari 100 intelektual termasuk Mochtar Lubis, H.B. Jassin, P.K. Ojong, Roshan Anwar, dan kepada generasi penulis anti-komunis yang lebih muda seperti WS. Rendra, Goenawan Mohamad, Taufiq Ismail, Soe Hok Gie, dan kakaknya Arif Budiman.[5]
Pendistribusian buku tersebut selain turut menyebarkan paham liberalisme dan anti-komunis, diungkapkan Kats sebagai respons atas minimnya jumlah penerbit yang berfungsi dan penurunan jumlah publikasi buku-buku baru yang “berkualitas baik”, selain itu juga karena Indonesia menurutnya sudah menjadi “comberan kebudayaan yang tersisihkan dari perdebatan intelektual secara umum dari negara-negara kaya.”
Pada tahun 1960an, sembari mengirimkan buku, Kats membangun hubungan erat dengan simpatisan PSI yang lebih muda, khususnya Goenawan Mohamad (GM). GM kelak menjadi tokoh yang paling berpengaruh di dalam mengokohkan liberalisme Barat dalam kebudayaan kontemporer Indonesia. Kedekatan GM dengan Ivan Kats juga terlihat dari korespondensi surat menyurat mereka yang juga sempat dibahas dalam tulisan Martin Suryajaya sebagai responsnya setelah membaca buku Wijaya Herlambang dan menghasilkan perdebatan dengan Goenawan Mohamad sendiri di Indoprogress.
Polemik Lekra dan Manifes Kebudayaan
Pengaruh dan dukungan CCF terhadap kelompok intelektual dan seniman anti-komunis seperti Wiratmo Soekito, H.B Jassin, Arief Budiman, Goenawan Mohamad, Taufiq Ismail serta penulis anti-komunis lainnya membuat mereka menemukan tempat untuk melawan dominasi arena politik-kebudayaan Indonesia yang saat itu didominasi oleh kaum kiri. Seniman kiri yang tergabung dalam sayap kebudayaan PKI, Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), juga memperkuat upaya mereka untuk mempromosikan gagasan komitmen politik di dalam seni dan sastra, sejalan dengan kampanye revolusioner Soekarno. Melihat peningkatan dominasi aktivitas seniman kiri, pada 17 Agustus 1963, kelompok H.B. Jassin mendeklarasikan sikap anti-komunisme melalui Manifes Kebudayaan—kemudian diplesetkan oleh kaum kiri dengan Manikebu, istilah peyoratif yang mengacu pada sperma kerbau dalam bahasa Jawa.
Isi dari deklarasi Manikebu sendiri, menurut Wijaya, sangat terpengaruh dan bahkan mirip dengan deklarasi CCF 1950 di Berlin dengan kebebasan intelektual dan artistik serta konsep humanisme universal sebagai moncong utamanya. Titik kemiripan pada dua deklarasi ini ada pada keyakinan dan kebebasan, di mana kebebasan tersebut tidak boleh disubordinatkan pada kepentingan atau “cita-cita yang paling agung atau tujuan tertinggi”, yang dalam konteks Indonesia saat itu adalah cita-cita politik revolusi.[6]
Hadirnya Manifes Kebudayaan 1963 di arena kebudayaan pada masa itu semakin menunjukan pengaruh dan campur tangan CCF untuk membangun pandangan anti-komunisme dan liberalisme Barat yang tertanam di lingkaran PSI, terutama generasi yang lebih muda seperti Goenawan Mohamad, Arief Budiman, Taufiq Ismail, dan lainnya -yang juga menandatangani Manifes tersebut.
Setelah polemik antara dua kelompok kebudayaan ini ditandai dengan saling berbalas tulisan di media massa antara penulis penyokong Manifes Kebudayaan dan Lekra, pada 8 Mei 1964, Presiden Soekarno melarang Manifes Kebudayaan dan basis ideologisnya, humanisme universal, karena dianggap sebagai bahaya bagi arah politik bangsa yang ingin melanjutkan revolusi melawan kekuatan-kekuatan kolonial.[7]
Serangan terhadap kelompok Manifes Kebudayaan lenyap seketika setelah setahun pasca pelarangan kelompok ini, meletus tragedi G30S 1965. Setelah peristiwa kudeta terhadap Soekarno pada 30 September, serangan tersebut berbalik arah di rezim otoriter Soeharto pada musuh Manifes Kebudayaan, Lekra beserta PKI dan sejawatnya. Bahkan lebih parah, pelarangan Lekra disertai dengan pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dituduh komunis oleh militer Indonesia di bawah komando Jenderal Soeharto pasca 1965.
Manifes Kebudayaan beserta penulis-penulis anti-komunis, menurut Wijaya, turut membenarkan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan rezim Soeharto terhadap orang-orang komunis dan yang diduga komunis. Ironisnya, produk kebudayaan yang membenarkan pembantaian itu digagas oleh mereka yang memiliki landasan ideologi humanisme universal yang seharusnya “berpihak pada kemanusiaan” alih-alih membenarkan pembantaian itu terjadi melalui produk-produk kebudayaan yang diciptakan.
Bubarnya CCF, terbitnya Horison
Hubungan gelap antara CIA dan CCF yang sebelumnya tidak diketahui secara gamblang akhirnya dibongkar oleh New York Times pada April 1966. Terkuaknya dukungan finansial CIA kepada CCF ini memaksa Michael Josselson, agen CIA yang menjabat sebagai Direktur CCF, mengundurkan diri dan lembaga ini pun dibubarkan.
Kendati demikian, CCF tidak sepenuhnya bubar sebab organisasi ini akhirnya hanya “berganti nama” menjadi International Association for Cultural Freedom (IACF). Pada September 1967, lembaga ini mengumumkan bahwa mereka tak lagi menerima dana dari CIA. Namun, pada praktiknya, IACF masih melanjutkan tujuan CCF, memberikan kontribusi penting bagi terbentuknya ideologi praktik kebudayaan di Indonesia yang bertujuan untuk menghancurkan komunisme, mencitrakannya sebagai setan, tirani, dan ancaman terhadap “kebebasan berekspresi” .
Ketika militer di bawah Jenderal Soeharto mulai mengendalikan politik Indonesia, para mahasiswa meminta tahanan politik anti-komunis di zaman Sukarno untuk dibebaskan, termasuk Mochtar Lubis. Pembebasan Mochtar Lubis ini dibarengi juga dengan Arief Budiman yang ingin mengakomodasi suara penulis anti-komunis dengan meluncurkan majalah sastra kebudayaan bernama Horison.
Horison yang meskipun menjadi majalah sastra paling berpengaruh pada awal Orde Baru dengan banyak menerbitkan karya sastra dari para penulis anti-komunis, mengalami krisis finansial yang akhirnya dibantu oleh IACF, melalui Mochtar Lubis yang juga Dewan Eksekutif lembaga ini, dengan memberikan bantuan dana tahunan sebesar US$10.000. Karya-karya sastra di Horison sendiri, menurut Wijaya, banyak dipengaruhi gagasan humanisme universal di mana konflik psikologis para tokohnya menjadi faktor utama dalam menaturalisasi kekerasan terhadap kaum komunis. Selain itu, dari enam cerpen yang dianalisis dalam bukunya, semuanya memiliki kecenderungan untuk mengajak pembaca bersimpati pada para pembunuh ketimbang pada para korbannya.[8]
Selain terbitnya Horison, IACF juga turut mendanai Yayasan Obor dibantu Rockefeller Foundation, Ford Foundation dan beberapa lembaga internasional lain. Yayasan Obor dan Horison, menurut Janet Steele, sangat berpengaruh dalam membentuk ideologi anti-komunis dalam aktivitas intelektual dan kebudayaan di Indonesia. Sementara itu, praktik kebudayaan kiri secara telak terhapus seiring dengan pembantaian komunisme oleh militer dan sekutu mereka.
Chairil Anwar dan Surat Kepercayaan Gelanggang
Hal yang mengejutkan lagi selain pencatutan nama-nama besar sastrawan di atas macam H.B Jassin, Goenawan Mohamad, Soe Hok Gie, dan sebagainya yang juga ternyata memiliki hubungan dengan CIA melalui CCF atau PSI, Wijaya juga mengatakan bahwa Chairil Anwar merupakan simpatisan PSI. [9] Hal ini diperkuat karena selain punya hubungan darah dengan Ketua PSI (keponakan Sjahrir), kelompok Gelanggang—yang juga diprakarsai oleh Chairil Anwar, Rivai Apin, dan Asrul Sani—turut mendeklarasikan pernyataan Surat Kepercayaan Gelanggang yang memiliki gagasan inti humanisme universal yang juga dianut oleh Manifes Kebudayaan setelahnya.
Pramoedya Ananta Toer menolak pandangan Surat Kepercayaan Gelanggang dan mencurigai bahwa agen-agen kebudayaan dalam kabinet Van Mook, seperti Rob Nieuwenhuys, Dolf Verspoor, dan mungkin A. Teeuw, memiliki tugas khusus untuk menginfiltrasi ideologi kebudayaan Indonesia dengan mensponsori, misalnya, majalah Siasat—yang di dalamnya terdapat ruang budaya Gelanggang, cikal bakal kelompok Gelanggang.
Selain itu, Deddy Arsya dalam artikel berjudul Fasisme, Sastra Zaman Jepang, Dan Upaya ‘Membunuh’ Chairil yang dimuat Padang Ekspress tahun 2014, mengatakan bahwa Sitor Situmorang pernah menuduh Chairil kontra-revolusioner karena sajak-sajak dan gaya hidupnya yang kebarat-baratan dan DN Aidit pernah menganggap Chairil ‘Ofensif revolusioner’, borjuis yang terasing dari bumi tanah air dan tidak berakar pada budaya nasional.
Lalu kritik juga datang jauh sebelum polemik Lekra dan Manikebu berkecamuk. AS Dharta pernah menulis esai “Angkatan 45 Sudah Mampus” di majalah Spektra tahun 1949 yang juga turut menjadi salah satu pemicu terbentuknya Lekra pada 17 Agustus 1950. Dalam esainya, ia kecewa dengan Angkatan 45 yang menurutnya tidak menjadi bagian dalam gelombang sejarah peristiwa Madiun 1948 dan menganggap dalam tubuh angkatan 45 merajalela anasir kelas pertengahan yang senang semboyan-semboyan hidup hampa, asal menggetarkan rasa. [10]
Sebelum menulis esainya yang mengkritik Angkatan 45, ia juga sempat menulis sajak untuk Chairil Anwar dengan nama pena Jogaswara:
“Dan engkau mengamuk/berani menghantam,
gempur segala/asal ngamuk, asal pukul/pukul! pukul! pukul!/jangan tanya karena apa, untuk apa…
Ach, Chairil!/Mengamuk semata untuk ngamuk/sama dengan mereka peminum candu: Nol Besar!”
Chairil Anwar, menurut Sapardi Djoko Damono dalam artikel yang ditulis Melani Budianta, memang sering berada di tangan orang-orang politik. Pada tahun 1965, Chairil menjadi ajang perkelahian dua kubu meskipun menurut Sapardi, Chairil “tidak memihak kegiatan politik pihak tertentu”. Klimaks pertentangan itu terjadi pada penolakan pencanangan tanggal 28 April sebagai Hari Sastra oleh pihak Lekra dengan alasan “bahwa gagasan kepenyairan Chairil Anwar bertentangan dengan paham Sosialisme Indonesia dan Amanat Berdikari yang digariskan Bung Karno.”
**
Pada akhirnya, saya pikir keterlibatan orang-orang yang sebelumnya pernah saya, atau kita, kagumi karya-karyanya yang membuka kita untuk mencintai sastra Indonesia ini tidak dapat sepenuhnya kita tinggalkan hanya karena memiliki keterkaitan dengan CIA, misalnya. Meskipun begitu, kita juga jangan menampik kenyataan bahwa memang sastrawan yang kita kagumi karya-karyanya itu memiliki hubungan dengan CIA dan melanggengkan kekerasan budaya melalui produk kebudayaan yang mereka ciptakan.
Mengutip Joel Whitney penulis FINKS: How the CIA Tricked the World’s Best Writers dalam wawancaranya bersama Vice, “kamu berhak dan pasti ingin tahu kebenaran soal kerja-kerja intelektual para penulis dan penerbit yang kamu cintai itu, serta tujuan-tujuan mereka sebetulnya. Bukan berarti mereka tidak lagi pantas untuk dikagumi, kan.”
Kendati keran kebenaran sudah dikucurkan dan mulai bermunculan sejak rezim otoriter Soeharto runtuh termasuk dengan terbitnya buku Kekerasan Budaya Pasca 1965 yang membuat kemapanan berpikir kita tentang sejarah morat-marit, pengaruh warisan Soeharto masih tetap terasa dan bercokol bahkan hingga kini. Riak air wacana Orde Baru masih terlihat dari maraknya isu PKI bangkit setiap bulan September, menuduh lawan politik PKI, sampai perayaan hari Kesaktian Pancasila—sebagai pembenaran monumental atas genosida pasca 65, karena menggunakan ideologi Pancasila sebagai landasan untuk membunuh PKI dan yang diduga PKI—yang sering dirayakan bahkan oleh beberapa kelompok mahasiswa, yang ironisnya sering mengkritik dan mengaitkan pemerintah sekarang dengan Orde Baru.
Inilah yang akhirnya membuat kekerasan budaya yang diproduksi pasca 65 dan sudah dipersiapkan sebelum 65 oleh agen-agen kebudayaan menjadi lebih berbahaya ketimbang kekerasan secara fisik, sebab kekerasan budaya yang tidak terlihat dan yang tidak disadari ini berhasil membuat masyarakat umum beranggapan bahwa komunisme adalah hal yang menakutkan dan membunuh, sekaligus membenci, “orang-orang komunis” adalah kewajaran bahkan keharusan.
Daftar Rujukan
Buku
Ulrich Kratz, Sumber Terpilih Sejarah Sastra Indonesia Abad XX (Jakarta: KPG, 2000)
Wijaya Herlambang, Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film (Jakarta: Marjin Kiri, 2013)
Jurnal
Lilik Salamah, 2008, Meninjau kembali konflik perang dingin: liberalisme vs komunisme. Jurnal Global dan Strategis Unair Vol. 2 No 2., hlm. 225-237.
Internet
Martin Suryajaya, Goenawan Mohamad dan Politik Kebudayaan Liberal Pasca 1965 https://indoprogress.com/2013/12/goenawan-mohamad-dan-politik-kebudayaan-liberal-pasca-1965/ diakses pada tanggal 15 November 2021.
[1] Lilik Salamah, 2008, Meninjau kembali konflik perang dingin: liberalisme vs komunisme. Jurnal Global dan Strategis Unair Vol. 2 No 2., hlm. 225-237.
[2] Wijaya Herlambang, Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film (Jakarta: Marjin Kiri, 2013), hlm. 60-62.
[3] Ibid., hlm. 58-59.
[4] Ibid., hlm. 65.
[5] Ibid., hlm. 78.
[6] Ibid., hlm. 85.
[7] Ibid., hlm. 89.
[8] Ibid., hlm. 94-103.
[9] Ibid., hlm. 72-73.
[10] Ulrich Kratz, Sumber Terpilih Sejarah Sastra Indonesia Abad XX (Jakarta: KPG, 2000), hlm. 166-171