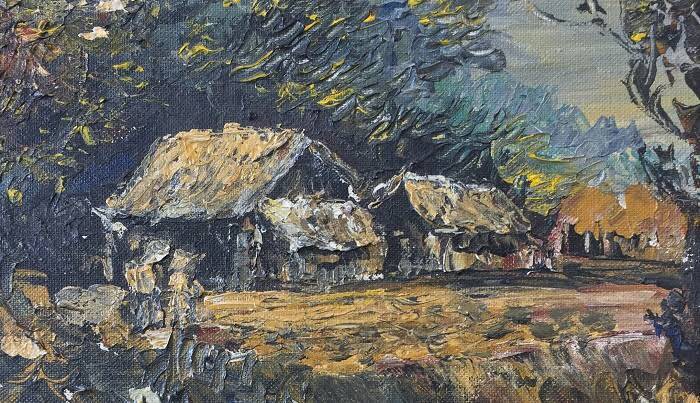Sumber foto: https://nusantaranews.co/dusun-kecil-untukmu/
Rumah kecil warisan Abah sekarang sudah dibangun berpondasi tembok yang dicat putih—meskipun di beberapa bagian telah mengelupas catnya—dan beratapkan asbes. Kakak-kakakku masih belum mampu membeli genteng, sedangkan cat rumah sendiri diberikan majikan kakak sulungku yang kebetulan habis merenovasi kamar anaknya.
Aku sudah duduk di bangku SMP, para tamu yang datang ke rumah kecilku tak pernah bertambah dari teman-teman bapak, ibu-ibu arisan, dan mahasiswa-mahasiswa kota. Mungkin tambah sedikit, teman-teman sekolahku. Kadang-kadang, ketika aku dan teman-temanku tengah bermain di rumah, para mahasiswa ini datang mencari ibuku. Duduk beberapa menit mengobrol sebelum akhirnya pergi dan tidak pernah terlihat lagi.
Suatu hari, temanku bertanya soal kedatangan anak-anak muda keren asal kota yang terlalu rutin ke rumahku. Kubilang, aku tidak tahu apa urusan mereka.
“Kamu enggak penasaran gitu, apa yang kiranya mereka inginkan? Coba, tugas macam apa yang mereka garap sampai terus datang ke rumahmu?” ucap temanku, Popi, mencoba membuatku tertarik.
“Tapi itu urusan orang dewasa.”
“Tapi kita juga bukan anak kecil, kita udah SMP!”
Tentu saja aku membenarkan pernyataan Popi barusan, sudah sewajarnya aku tahu alasan para mahasiswa itu sering datang ke rumah karena aku bukan anak kecil lagi.
“Konon katanya, para wanita yang bekerja untuk memuaskan tentara Jepang itu bersembunyi di beberapa desa yang dirahasiakan baik nama maupun keberadaannya. Sebab, fakta tersebut cukup memalukan bagi wanita-wanita mantan Jugun Ianfu,” jelas Bu Uti, guru IPS-ku.
“Wah, berarti bisa jadi nenek saya juga bagian dari Jugun Ianfu, ya, Bu?” Rusdi, si anak lelaki yang banyak bicara itu menyahut.
“Bisa jadi, tidak ada yang mustahil,” jawab Bu Uti dengan candaan sebelum ia mengakhiri pelajaran hari ini.
Candaan Bu Uti tersebut terus teringat dipikiranku, bisa jadi urusan mahasiswa-mahasiswa tersebut bertamu ke rumahku karena alasan ini. Sialnya, aku tidak pernah tahu mereka ini mahasiswa yang menekuni bidang apa.
Sore itu, setelah pulang sekolah dan membantu Ibu jualan, aku duduk di teras depan rumah sambil membuat adonan cilok. Nenekku yang sudah semakin tua duduk tak jauh dari tempatku sambil menyirih, jarang sekali ada rombongan mahasiswa yang datang di sore hari. Kalau aku tak bisa bertanya kepada mereka yang tak menentu datangnya, aku bisa tanya pada nenekku.
Kubawa boskom berisi adonan ke dekat nenekku, agaknya ia kaget sebelum bertanya, “Ada apa, Nak?”
“Nenek tau Jugun Ianfu?”
Mulutnya yang tengah mengunyah sirih terhenti, kedua matanya yang sayu melotot walau tak kentara. “Tau dari mana toh, Nak?” ia balik bertanya, melepeh sirih dari mulutnya. Kukira nenekku sudah tidak punya lagi gigi, ternyata masih ada sebagian karena ia mampu mengunyah sereh.
“Guruku memberitahu di sekolah. Jadi, Nenek tau tidak?” tanyaku tak sabaran.
“Mana tau, Nenek gak sekolah, Nenek bodoh,” jawabnya sambil berlalu ke dalam rumah. Rasanya aneh juga kalau nenekku tidak tahu soal Jugun Ianfu, bahkan tidak penasaran seperti biasanya kalau aku sudah cerita. Nenekku sebelumnya bahkan pernah bercerita kalo ia hidup dari zaman penjajahan.
“Permisi…” suara yang berasal dari halaman depan menyadarkan lamunanku, seorang perempuan berhijab hitam dengan satu temannya berniat bertamu. Aku tahu, pasti mereka mahasiswa.
Dengan riang kuhampiri mereka. Duh, kebetulan sekali. “Cari siapa, Teh?” tanyaku.
“Rumahnya Ibu Tuti, benar kan ini?”
Aku mengangguk, mempersilakan keduanya duduk di teras rumahku, “Ibu belum pulang, Teh, sedang ke kebun.”
“Enggak apa-apa, kita bisa tunggu,” jawab temannya. Segera aku bergegas ke dalam, membuat dua gelas air dan beberapa cemilan ala kadarnya. Kulihat nenekku sedang melipat baju di ruang tengah, “Ada tamu.”
“Cari siapa?” tanya nenekku dengan suaranya yang agak kurang jelas.
“Mahasiswa, Nek, cari Ibu.”
“Suruh saja pergi,” aku mengernyit. Kok begitu? Aku tidak pernah diajarkan memperlakukan seseorang secara tidak santun, jadi aku hanya melenggang pergi memutuskan membiarkan kedua mahasiswa tersebut menunggu Ibu.
Mereka berterima kasih dan meminum tandas air yang kusuguhkan, kelihatannya mereka capek. Keduanya memperkenalkan diri, yang berhijab namanya Andin, sedangkan temannya Siska. Mereka berdua mahasiswa. Perjalanan yang tidak menyenangkan membuat mereka akhirnya tiba di waktu sore, katanya ini di luar rencana.
“Teteh-teteh ini mahasiswa apa?” Kutanya hati-hati sambil membentuk adonan cilok bulat-bulat.
“Jurusan Sejarah,” jawab Teh Andin.
“Kalo boleh tau, ada perlu apa datang menemui ibu?” aku menatap keduanya yang terlihat agak kebingungan.
“Tugas akhir, Dek,” hanya itu yang diucapkan Teh Siska, itupun dengan enggan jawabnya, jadi aku segan kembali bertanya.
Ibu datang tak lama kemudian, aku yang sudah selesai membentuk adonan segera berpamitan pergi ke dalam rumah. Ibuku mempersilahkan keduanya masuk. Setelah kusimpan adonan cilok, diam-diam aku menguping.
“Saya tau maksud kalian, Adik-adik, tapi maaf sekali Ibu tidak bisa membantu sebab topik yang ingin kalian bahas tidak lain dari aib keluarga kami. Jadi, mohon maklumi keputusan kami.”
Aib? Aib apa? Tanyaku dalam hati. Kedua mahasiswa itu mencoba membujuk Ibu, tapi Ibu terus berkeras hingga akhirnya mereka berpamitan dan memutuskan untuk datang esok hari lagi.
“Ibu, bagaimana kalo Teteh-teteh ini disuruh menginap saja? Sudah keburu malam dan tidak banyak kendaraan,” usulku sebelum keduanya benar-benar keluar dari rumah kecilku. Mau tidak mau ibuku mengizinkan.
Kujadikan ini sebagai percobaan keduaku untuk mengorek soal aib yang Ibu maksud. Rasanya tidak mungkin aku bertanya pada Ibu yang merahasiakan aib ini rapat-rapat. Jadi, satu-satunya harapan adalah teteh-teteh mahasiswa ini. Keduanya dipersilakan untuk tidur di kamarku, walaupun kasurnya tidak terlalu besar, tetapi cukup menampung ketiga perempuan dengan perawakan kecil seperti kami.
“Teteh tau Jugun Ianfu?” tanyaku kepada keduanya, mereka baru saja selesai mandi dan tengah berbenah.
“Tau, dong,” jawab Teh Siska. “Kenapa, Amel?”
“Iya, Amel juga belajar itu. Memangnya benar kalo wanita-wanita seperti itu masih ada?”
“Masih, mungkin banyak tapi mereka menyembunyikan identitas karena fakta tersebut aib untuk yang bersangkutan,” jawab Teh Siska.
“Kok aib sih, Teh? Kan mereka juga tidak berkehendak atas peristiwa tersebut, mereka korban, harusnya mereka mau buka suara.”
Teh Siska mengusap kepalaku lembut, “Kalaupun bersuara, peristiwa tersebut tidak dapat diadili karena sudah lama berlalu. Di tengah masyarakat Indonesia yang religius, pekerjaan semacam itu dianggap tidak terpuji dan yang terlibat bisa dikenakan sanksi sosial. Makanya, itu aib, sayang…”
Aku terdiam lama mencerna penuturan Teh Siska barusan. Teh Andin yang sedari tadi sibuk mengutak-atik ponselnya bersuara, “Kita juga harus menghargai keputusan dan masa lalu seseorang, hidup akan terus berjalan.”
Itulah percakapan terakhir sebelum kami memutuskan untuk segera tidur, percakapan yang tidak menjawab pertanyaanku.
Teteh-teteh mahasiswa itu berpamitan setelah subuh. Mereka mengobrol dengan Ibu dan Bapak di ruang tamu, tidak banyak membahas soal tujuan mereka datang kemari. Kupikir keduanya sudah sepakat untuk menghargai aib keluarga kami dibanding kepentingan tugas mereka, apalagi sudah diizinkan untuk menginap.
Ketika Bapak telah berangkat ke ladang, tinggalah aku, Ibu dan Nenek di ruang tengah. “Bagaimana kalo Nenek ternyata salah satu korban tentara kolonial?” celetukanku barusan membuat ibuku yang sedang asyik mengemas cilok terhenti, begitupula nenekku yang sedang asyik menyirih.
“Kalo memang betul begitu, ingat pesan Teteh-teteh kemarin malam, hargai setiap keputusan dan masa lalu seseorang,” jawab Ibu sebelum ia melanjutkan, “Begitu pula keputusan Ibu yang tidak ingin membicarakan soal itu, ada saatnya kamu tau. Amel ‘kan anak pintar.”
Aku terdiam. Kukira aku tidak perlu lagi ikut campur urusan orang dewasa, merepotkan dan membuat kepalaku pusing. (Irn/Zai)
***